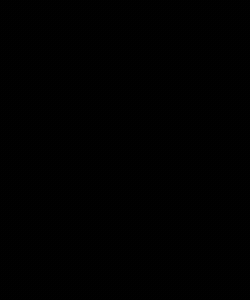NEWSATU.COM – Graziano Mannari punya momen favorit di San Siro, dan tak ada yang bisa menyalahkannya. Momen itu terjadi pada Maret 1989, saat ia masuk sebagai pemain pengganti ketika AC Milan sudah unggul dua gol atas Juventus. “Penonton benar-benar dalam mode pesta,” kenangnya kepada Sky Sports.
“Mereka meneriakkan ‘olè’ setiap kali kami mengoper bola. Bola mengalir indah di antara seluruh tim—Franco Baresi, Mauro Tassotti, Carlo Ancelotti, Marco van Basten—berulang kali, dan setiap sentuhan memancing gemuruh ‘olè’ dari tribun.”
“Dalam hati, saya berpikir, ‘Saya hanya ingin menyentuh bola sekali saja, agar saya juga dapat teriakan olè!’. Tapi bola tak kunjung datang ke arah saya—sampai Roberto Donadoni melepaskan umpan silang sempurna. Saya melompat, menyundul sambil menjatuhkan diri, dan bola bersarang di pojok atas gawang.”
“Kali ini tidak ada teriakan lembut ‘olè’—stadion meledak dalam gegap gempita yang luar biasa. Saat mendarat, saya seolah tak percaya telah mencetak gol. Teman-teman setim langsung menyerbu untuk memeluk saya. Tak lama kemudian, saya mencetak gol lagi untuk skor 4-0. Itu adalah sebuah mimpi.”
Memori Mannari hanyalah satu dari ribuan momen spesial di San Siro. Sebulan setelahnya, AC Milan menghancurkan Real Madrid 5-0 di semifinal Piala Champions, sebuah laga yang menandai pergeseran kekuatan sepakbola dunia menuju era dominasi Italia di benua biru.
Tahun berikutnya, San Siro menjadi saksi bisu saat Kamerun mengejutkan Argentina-nya Diego Maradona di laga pembuka Piala Dunia 1990. Sejak diresmikan tahun 1926 dengan kemenangan Inter 6-3 atas Milan, stadion ini telah menjadi rumah bagi pertandingan besar, momen legendaris, bahkan foto-foto ikonik.
Foto lama Rui Costa (Milan) dan Marco Materazzi (Inter) yang berdiri berdampingan melihat asap flare yang membara di dalam San Siro telah menjadi simbol. Persatuan dan perpecahan. Beauty and the Beast. Foto itu merangkum sepak bola Italia pada titik paling provokatif sekaligus paling rapuh.
Kapten legendaris Inter, Javier Zanetti, bermain dalam laga itu. “Ini akan selalu menjadi stadion yang membawa kenangan,” katanya. “Dan membawa banyak kemenangan.” Momen favorit pribadinya adalah debutnya. “Saya tidak pernah membayangkan itu adalah laga pertama dari total 858 pertandingan.”
Christian Eriksen melakoni debut Serie A-nya untuk Inter di Derby della Madonnina. “Stadion ini luar biasa,” katanya. “Sisi Milan dan sisi Inter, curva yang berbeda. Sejarahnya berbicara sendiri.”
Bagi Mannari, sejarah itu melambangkan sepak bola sebagai budaya tinggi. Ia membandingkannya dengan La Scala (gedung opera terkenal di Milan). “Sama seperti gedung opera Milan yang menggelar pertunjukan terindah dan seniman terhebat, stadion ini telah mementaskan tampilan sepak bola terbaik,” ujarnya.
Hitung Mundur Kehancuran
Namun, satu abad setelah semuanya dimulai, jam terus berdetak untuk San Siro. Rencana untuk merobohkannya sudah ada di depan mata.
“Mereka sudah mengatakan itu selama 10 tahun terakhir,” kata Eriksen dengan nada sedikit tak percaya. Namun kali ini, rencana tersebut semakin nyata setelah dewan kota menyetujui penjualannya.
Milan dan Inter kini menjadi pemilik sah, berbagi hak dan tanggung jawab atas pembangunan stadion baru yang akan dibangun tepat di sisi barat lingkungan San Siro. “Semoga mereka mempertahankan sebagian dari stadion lama,” harap Eriksen.
Itu memang bagian dari rencana.
Wajar jika ada rasa haru. Kata “ikonik” mungkin sudah terlalu sering digunakan, namun bagaimana lagi cara mendeskripsikan San Siro? Meski Wembley atau Maracana punya kekuatan sendiri, San Siro adalah stadion yang melekat kuat di memori visual.
Menara beton yang melingkar ke langit, tiang merah yang menonjol membuatnya tampak seperti pesawat luar angkasa yang sedang dibangun. Stadion ini seperti katedral, dirancang untuk menginspirasi kekaguman.
“Bermain di San Siro, dengan tribun melingkar yang menjulang tinggi dan menekan dekat ke lapangan, rasanya seperti melangkah ke dimensi lain. Anda bahkan tidak bisa mendengar suara sendiri saat bicara dengan teman setim—Anda harus berteriak,” jelas Mannari.
“Tanahnya benar-benar bergetar saat penonton bersorak kegirangan atau bersiul mengejek. Itu adalah sensasi unik yang tak tergambarkan. Kecuali Anda mengalaminya sendiri, sulit untuk membayangkannya. Ini adalah stadion terindah tempat saya pernah bermain.”
Menjawab Tuntutan Modernitas
Andrew Edge, seorang arsitek spesialis desain stadion dari Arup, memahami dilema ini. “Stadion adalah panggung yang memungkinkan penggemar mengalami pertandingan yang tak terlupakan. Sangat penting untuk menghargai hubungan emosional yang kuat antara penggemar dan stadion lama saat mendesain yang baru.”
Rencananya, sebagian dari tribun tingkat kedua akan digunakan dalam konstruksi San Siro baru. “Ciri khas seperti atap merah atau ramp spiral adalah DNA stadion ini. Anda harus menggunakan itu sebagai inspirasi,” kata Edge.
Perubahan ini memang dibutuhkan. Salah satu pemicunya adalah fakta bahwa San Siro saat ini dianggap tidak layak menjadi tuan rumah Euro 2032. Hal yang tak terbayangkan sebelumnya, namun itulah konsekuensi modernitas.
Meski sedih, tokoh seperti Zanetti yang kini menjadi Wakil Presiden Inter memahami kebutuhan ini. “Segalanya telah berubah,” jelasnya. “Tim sepenting Inter membutuhkan stadion baru yang mutakhir. Yang penting, stadion itu akan tetap di area San Siro. Saya berharap kita bisa menciptakan memori spesial di sana juga.”
Dan San Siro—versi baru atau lama—akan kembali menggema dengan teriakan ‘olè’ sekali lagi.***